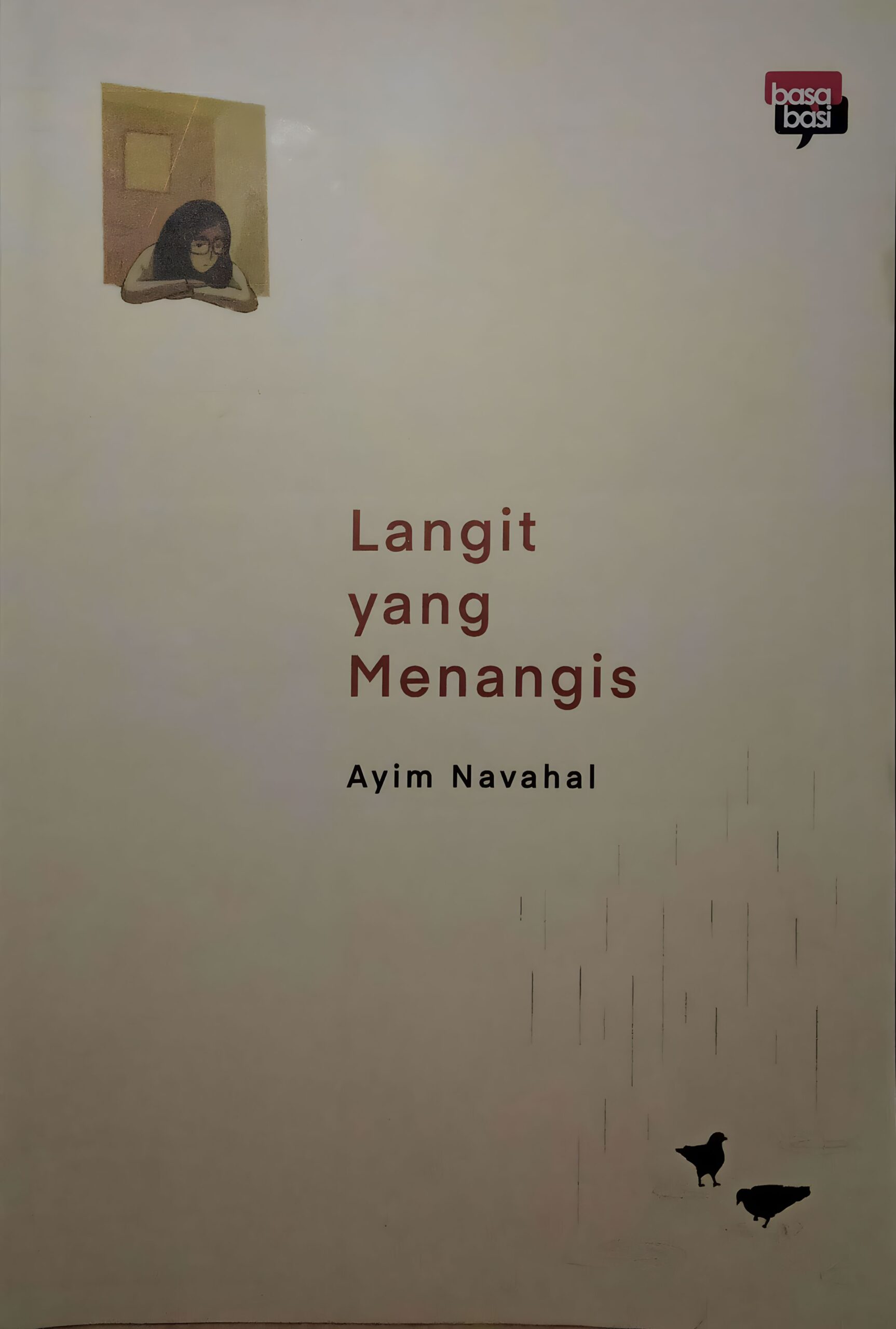Kehidupan pesantren sering kali diidentikkan dengan miniatur kultur patriarki. Hal ini tidak lepas dari dinamika pendidikan pesantren yang bias gender. Sebab, tidak lepas dari dominasi sosok laki-laki (baca: kiai) sebagai pemegang otoritas tunggal. Buku yang terdiri dari 14 bab ini mencoba mendobrak kultur patriarki yang mapan di pesantren.
Navahal memosisikan Safaa, tokoh utama dalam novel Langit yang Menangis, ini dengan sikap tegas menyuarakan hak-hak perempuan. Namun, posisinya sebagai perempuan yang tumbuh di lingkungan pesantren membuatnya tidak melupakan tradisi ketaatan dan penghormatan terhadap lelaki. Sebab, semua dilakukan dengan berlandaskan ajaran Islam, khususnya perilaku sufistik.

Merujuk Syarifah (2018: 64), feminisme sufistik dalam perspektif pendidikan karakter adalah mengembalikan hak-hak perempuan untuk berpendapat, memiliki kekayaan, berkarya, hak waris, dan memperoleh pendidikan. Sehingga, perempuan memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan diri, namun tetap menjaga moralitas dalam ketaatan kepada tuhan, ayah, dan suami sebagai kepala rumah tangga.
Langit yang Menangis dibuka dengan sebuah pertanyaan yang menyiratkan bagaimana kecondongan Navahal terhadap isu gender. Dari kondisi seperti inilah novel kedua Navahal setelah di tahun 2018 menelurkan buku kumpulan puisi pertamanya, Lentera Hati, tersebut tidak jauh dari tujuan menyuarakan hak perempuan. Sebagaimana hal yang diungkapkan Safaa dalam kutipan dialognya:
“Misal laki-laki menodai perempuan. Yang rugi perempuannya kan, Mas? Tapi di dalam etnik masyarakat kita justru perempuanlah yang terhinakan. Lalu kesalahan besar lelaki terlupakan sedangkan perempuan akan menanggung noda dan beban sepanjang hidupnya….” (hlm. 6)
Kemudian dipertegas dalam dialog: “Menjadi perempuan pesantren tidak pasti tentang perjodohan satu sisi kan, Buk?” Lalu dijawab oleh Gus Ali, kakak pertama Safaa, “Ya, kamu hidupnya di pesantren. Misal kamu hidup di bumi, kamu ya harus menaati tata aturan di bumi.” (hlm. 24)