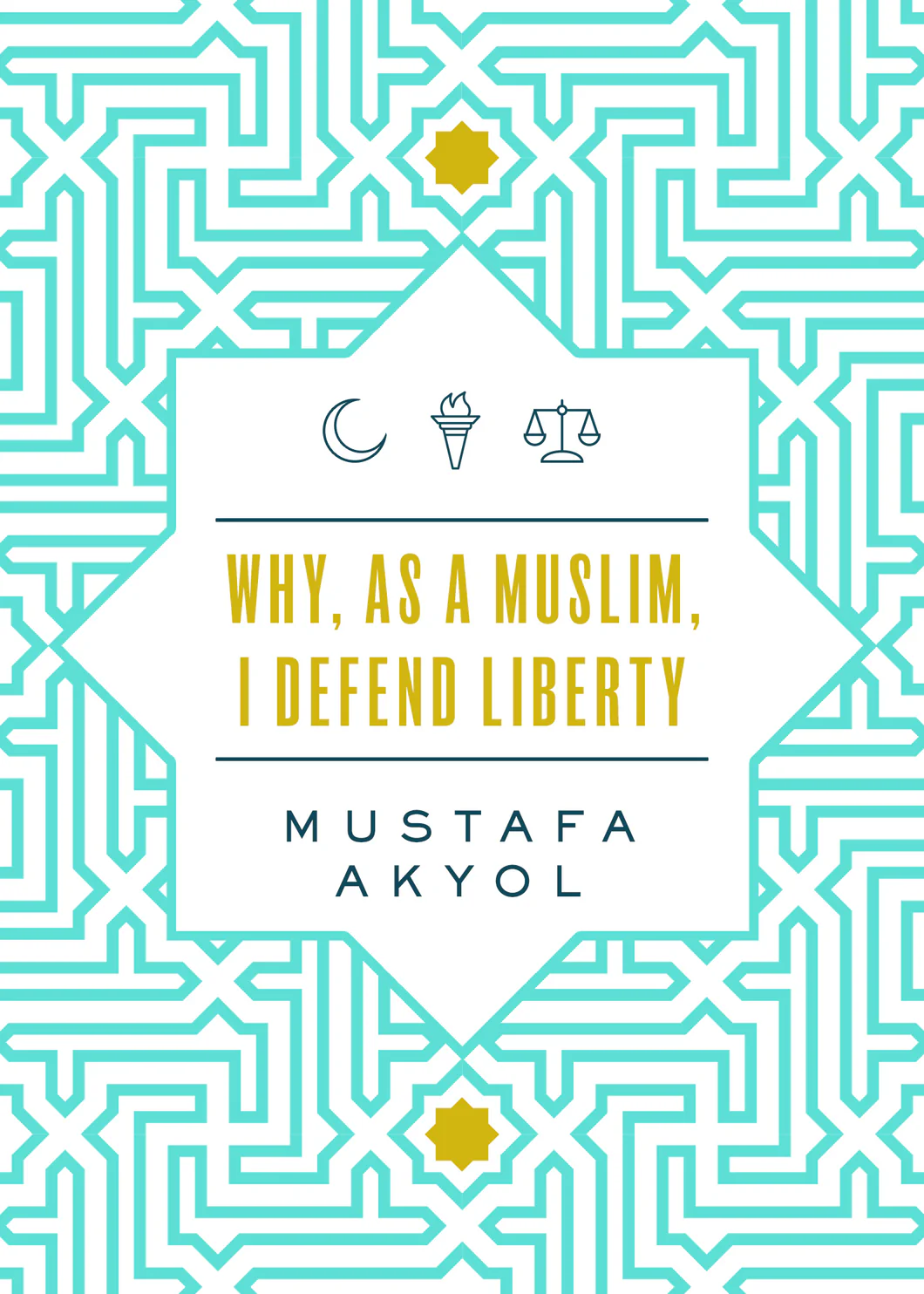Saya tidak kaget tatkala Ahmet T. Kuru, salah seorang penulis Turki prolifik, berhadapan dengan polisi di Negeri Jiran pada awal tahun 2024. Bahkan ketika bulan lalu buku-bukunya dimasukkan daftar hitam oleh lembaga fatwa Malaysia, saya hanya tersenyum getir. Sebab, jauh sebelum Kuru, saya tahu nama penulis berdarah Turki lain, Mustafa Akyol, pernah menghadapi kejadian serupa di tahun 2017.
Kronologi perseteruan dengan otoritas setempat terekam dengan baik di bagian pengantar salah satu karya Akyol yang masyhur, Reopening Muslim Minds: A Return to Reason, Freedom, and Tolerance (New York: St. Martin’s Press, 2021), dengan tajuk ‘Suatu Malam Bersama Polisi Agama’.

Apa yang menimpa kedua penulis berdarah Turki tersebut memberikan lanskap menarik kepada khalayak bahwa di sebagian negara dengan mayoritas umat Islam, tindakan represif terhadap ide non-mainnstream adalah hal lumrah.
Sindiran Akyol, pelarangan buku lebih mudah daripada kontra-argumen terhadap narasi-narasi yang dianggap tidak Islami (un-Islamic speech). Tindakan yang terakhir ini membutuhkan upaya untuk mempelajari, memikirkan kembali, dan mengartikulasikan ide. Padahal, langkah tersebut merupakan cara paling ideal untuk mewujudkan dunia Muslim yang lebih kreatif. Namun, sebelum merealisasikan itu, kebebasan adalah prasyarat mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu (hlm. 90).
Pada buku yang relatif tipis ini, diakui penulisnya sebagai pengantar terhadap isu Islam dan kebebasan. Semua pembahasan dalam delapan babak menjurus pada satu topik besar. Penyampaian ide yang digunakan juga lebih mudah dicerna pembaca secara general, mengingat ia mencoba untuk “elucidating complex ideas with personal anecdotes, historical episodes, and thought experiments, which I am sharing for the first time.”
Kemampuan story-telling Akyol memang patut mendapat ancungan jempol. Amunisi ini kerap ia pakai untuk memulai tulisan dan kuliahnya: bertolak dari cerita-cerita sederhana yang memantik perenungan mendalam.
Pada bagian pengantar, misalnya, Akyol menarasikan pengalamannya saat perjalanan pulang dari Arab Saudi. Ia melihat bagaimana perempuan-perempuan berdarah Arab menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian hitam. Ketika pesawat hendak mendarat di Istanbul, tiba-tiba mereka keluar dari lavatori dengan pakaian serba terbuka.
“Salah seorang perempuan, bisa saya katakan, memakai rok mini paling pendek yang pernah saya lihat,” ungkapnya.
Dengan tegas ia katakan bahwa kita tidak bisa menilai mereka sebagai orang hipokrit, mengingat mereka tidak punya pilihan bebas di Arab Saudi untuk menggunakan pakaian terbuka.
Kejadian semacam itu tidak hanya terbatas di Arab Saudi. Negara-negara Muslim lain juga mengalami simtom yang serupa. Di mana negara mendikte suatu doktrin atau pakem tertentu yang ketika itu dilanggar bisa mempunyai implikasi legal. Pada titik tersebut, kebebasan telah raib dan yang tersisa hanyalah pemaksaan.
Sebabnya, secara singkat Akyol mendefinisikan kebebasan (liberty) sebagai ‘tidak adanya pemaksaan yang bersifat koersif’. Perihal ini saya jadi teringat Khaled Abou El-Fadl—salah seorang yuris kenamaan di Univeristy California Los Angles (UCLA)—yang membagi otoritas menjadi dua, koersif dan persuasif. Sementara yang pertama ditaati karena posisi strukturalnya, otoritas yang kedua ditaati karena kompetensinya.
Yurisprudensi Abad Pertengahan: Kemunculan dan Prospek
Mula-mulanya, Akyol mendasarkan argumen kebebasan ini berdasarkan penggalan surat Al-Baqarah yang banyak dikutip para sarjana pendukung kebebasan beragama. ‘Tidak ada paksaan di dalam agama’ dapat kita temui ketika mendiskusikan topik kebebasan, tanpa terkecuali di buku ini.
Menariknya, Akyol menyadari bahwa butuh upaya lebih dari sekadar merepetisi penggalan ayat tersebut, yakni dengan memikirkan kembali syariat Islam. Ia menyadari betapa sebagian interpretasi dari syariat kerap mencederai nilai-nilai luhur dan hak asasi manusia itu sendiri. Sebenarnya, perspektif ini sudah ia ketengahkan 14 tahun lalu pada salah satu kuliahnya di TEDxWarwick.
Ia kemudian mengajukan satu rangkuman pendek pada apa yang disebut sebagai ‘Yurisprudensi Pasca-Qur’an’ dengan titik fokus pada pertanyaan seputar kemunculan tradisi hukum Islam pada abad pertengahan.
Singkatnya, di masa tersebut, praktik-praktik keagamaan bersinggungan erat dengan kedaulatan negara, maka mengkreasikan hukum merupakan hal yang krusial. Kendati demikian, ketika para pakar hukum mencoba untuk merujuk pada Qur’an dalam proses legislasinya, hanya sedikit ayat yang mempunyai konten bernuansa hukum. Karena itulah, merujuk pada tradisi Pasca-Qur’an (baik itu hadis atau bahkan penalaran akal) adalah pilihan yang tidak terhindarkan.
Selanjutnya Akyol mencoba untuk mengurai preferensi para yuris dalam mengkreasikan hukum yang bersifat memaksa. Ia berpendapat bahwa paksaan yang bersifat koersif merupakan hal lazim pada saat itu. Imperium-imperium Gigantis (Bizantium dan Sasaniyah) juga memaksakan agama resmi mereka dan bahkan mengganjar hukuman mati bagi pelaku apostasi.
Ia kemudian memungkasi bahwa kita tidak dapat menilai hal tersebut keliru berdasarkan kacamata hari ini. Persoalannya terletak pada sebagian orang yang menganggap bahwa standar tersebut tidak lekang oleh waktu serta bisa diimplementasiakan kapan saja mengingat hal tersebut dimandatkan oleh syariat (hal. 38).
Sayangnya, pada bagian ‘apa yang harus dihidupkan kembali dari syariat?’ (chapter 3), gagasan Akyol sangat trivial dan terkesan mengulang banyak sarjana hukum Islam. Intensi (maqasid) dari syariat merupakan hal krusial yang harus dihidupkan, tulisnya. Alih-alih pengaplikasian hukum Islam secara literal sebagaimana termaktub dalam kitab klasik, pemahaman terhadap spirit di baliknya yang harus dihidupkan kembali. Sebuah gagasan yang telah banyak disuarakan oleh sarjana Muslim, utamanya para maniak kajian maqasid al-syariah. Dengan kata lain, tepat di bagian ini tidak ada hal yang benar-benar baru.
Sebagai pamungkas, Akyol menyudahi buku ini dengan pertanyaan apakah isu kebebasan merupakan konspirasi Barat. Nampaknya, tanpa menyelam lebih dalam, kita akan sangat mudah mengendus bahwa pertanyaan tersebut merupakan sanggahan terhadap pandangan yang selama ini banyak beredar. Seolah-olah ia hendak mengatakan bahwa isu ini bukanlah semata-mata konspirasi pihak asing. Kendati demikian, ia memahami mengapa umat Islam bersikap permisif terhadap gagasan kebebasan. Tidak lain disebabkan satu kata yang banyak mengubah tatanan dunia Islam sejak abad ke-18 dan 19: kolonialisme.
Agenda-agenda kebebasan yang diusung oleh Barat di saat yang sama justru menjadi sarana justifikasi ekspansi kolonialisme mereka. Pada abad ke-19, misalnya, sementara orang Inggris menyebutnya sebagai ‘beban tanggung jawab orang kulit putih’ (white man’s burden), di Prancis dikenal sebagai misi memperadabkan (civilizing mission). Sebagai konsekuensi logis, wilayah-wilayah non-Eropa—yang dalam tesmak mereka masih dipandang primitif—harus diselamatkan. Tidak ayal manakala Prancis menguasai Afrika Utara pada rentang waktu 1830 dan 1962, setelah sebelumnya mengokupasi Mesir dalam waktu yang relatif pendek.
Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, maka dapat dipahami mengapa umat Islam mempunyai pandangan bahwa liberalisme erat dengan kolonialisme. Dalam bahasa yang dipakai Akyol, terdapat suatu memori historis yang membuat umat Islam menggandengkan keduanya. Ditambah realitas faktual bahwa sebagian pemikir liberal, kendati tidak semuanya, justru menjadi pendukung praktik-praktik kolonialisasi. Walaupun begitu, terdapat dua hal yang dilupakan oleh umat Islam terkait hal ini.
Pertama, bahwa para pendahulu kita—Muslim liberal awal—menggunakan konsep yang sama untuk melawan hegemoni Barat. Kedua, mereka juga ingin mengembangkan konsep kebebasan di tanah mereka, semata-mata karena melihat bahwa kebebasan merupakan resep manjur di balik majunya peradaban Barat.
Untuk contoh yang pertama, Akyol menyebut nama Abd al-Rahman al-Jabarti (m. 1822) dan perlawanannya terhadap penjajahan Prancis. Generasi setelahnya, ada Rifa‛a al-Tahtawi (m. 1873) yang mengelaborasi lebih detail konsep hurriyat yang sebelumnya hanya sebagai antonim dari perbudakan. Di tangan al-Tahtawi, terminologi tersebut digunakan untuk kebebasan politik, sipil, hingga ekonomi.
Akyol juga menyebut dua nama Muslim liberal di Turki dan Tunisia, Namık Kemal dan Khayr al-Din. Bagi nama yang pertama, sama sekali tidak ada masalah belajar dari tradisi Barat, untuk kemudian membantu Muslim menemukan konsep yang sama di dalam Islam. Kemal sendiri sangat dipengaruhi oleh filsafat-nya Montesquieu di samping kegemarannya akan tradisi Islam. Ia dan koleganya berhasil mensintesiskan tradisi keislaman dan gagasan kebebasan ala Barat. Sementara itu, Khayr al-Din menilai bahwa kemajuan di Barat disebabkan oleh rasionalitas mereka, suatu hal yang banyak dihindari di dunia Islam.
Dengan kata lain, meskipun ide tersebut berasal dari Barat, namun dunia Muslim telah lama bersinggungan dengannya. Ironisnya, jejak-jejak tersebut masih jauh panggang dari api untuk bisa menjadi pemikiran arus utama. Faktanya, terminologi ‘liberal’ masih menjadi pantangan di kalangan umat Islam.
Di tengah keengganan tersebut, buku ini menemukan signifikansinya. Tidak berlebihan manakala saya ibaratkan gagasan kebebasan di dunia Islam sebagai barang antik di ruang gudang yang terkunci, dan buku inilah sebagai pembukanya.
Data Buku:
Judul : Why, As A Muslim, I Defend Liberty?
Penulis : Mustafa Akyol
ISBN : 978-1-952223-18-1
Penerbit : Cato Institute
Tahun : 2021
Tebal : 201 hlm.