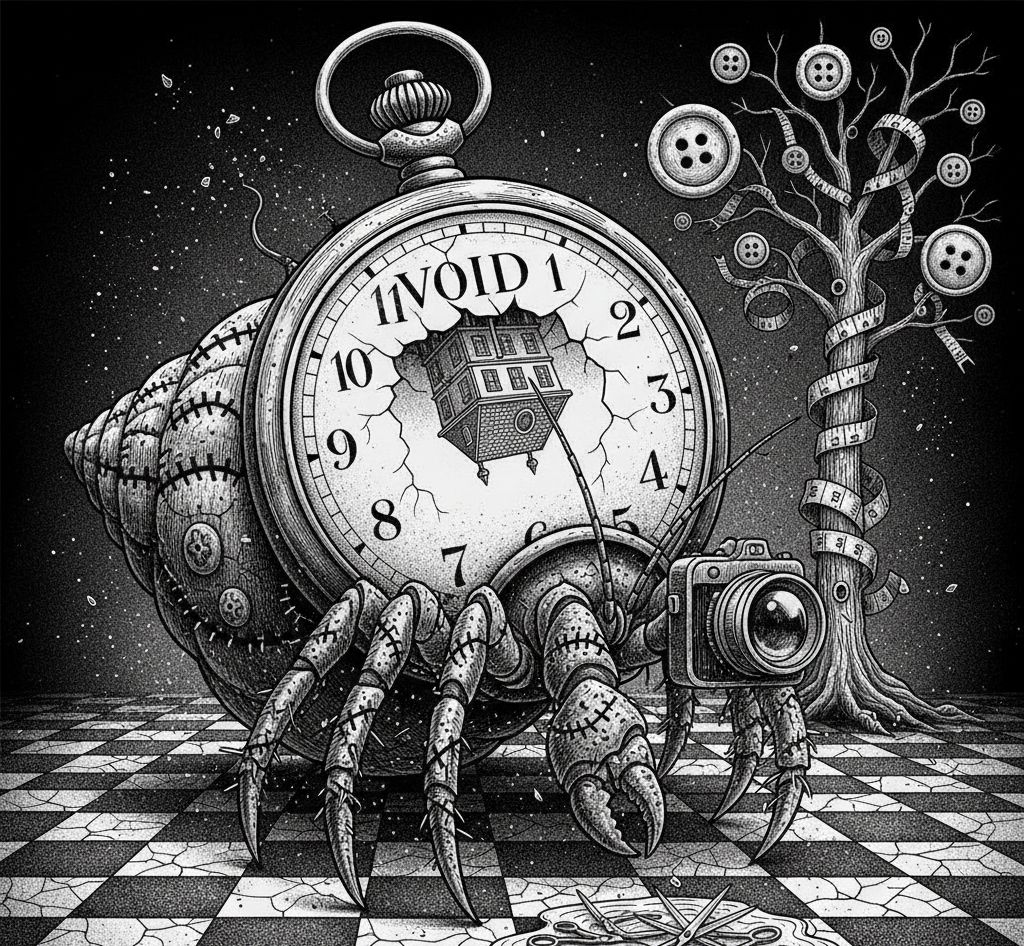HIMNE KEPADA ALKIMIA KATA
Kata-kata merembes
seperti cairan merah
menyentuh tepian taman.
Kemarilah,
huruf yang berbaris tegak
telah berubah bunga,
menatap kursi kayu
yang menjadi penanda
di dalam ada.

Rol kertas meluncur
melewati lampu berkedip
bersembunyi dalam kelopak malam
yang menggelembung.
Mendekatlah,
pena sudah menjelma
nisan kecil yang menghadap
bangku kosong,
menunggu gelisahmu.
Tetapi jangan takut
telinga menggantung pada pohon
menadah isyarat,
yang tak pernah punya akar.
Kau bisa salah dengar vokal,
atau bersenggolan
dengan konsonan berbulu,
jaraknya selalu tipis
antara jatuh dan melayang.
Duduklah dan lihat,
sebuah kata menepi
di sudut jalan,
menggigil
sebelum melompat
ke bibir halaman,
biarkan napasmu
menjadi angin,
meniup punggung koran
yang membuka rahasianya perlahan.
Ketika akhir dunia tiba,
cukup tutup mata,
dan tunjukkan pintu
di belakang kepala,
kalimat akan mengerti.
NAGA KECIL
Di tepi sutera langit,
seorang anak
menggambar lingkaran
dari napas pertamanya.
Ia menaruh puing petir
ke dalam mulut naga kecil
agar bisa bahasa hujan,
pisau, dua lapis jantung,
besi atau arus listrik.
Setiap kata yang keluar
menjadi sisik, menjadi hijau,
menjadi taring dari sejarah
yang melebur
di bawah bintang-bintang.
Suatu malam,
naga kecil itu
menelan peperangan
dan melihat dirinya pecah
menjadi ribuan matahari
tanpa hutan, jauh di selatan.
“aku bukan ciptaan,”
katanya pada pembuatnya,
“akulah kesalahan
yang menemukan makna.”
Lalu bumi mendengar,
dan mulai berputar lebih lambat.
TOPLESKACA SOCRATES
Kepala ini pecah
oleh paradoks padat
maupun cair, bisa basah,
kering, keras, lunak,
mengembang,
dan mudah berubah.
Aku menatap seekor semut
berjalan di jaringan udara,
sangat rumit, berongga,
dan menimbang kebenaran
sebelum jatuh ke lidahku.
Di dalam toples itu,
logika menjelma ikan,
tapi membatu,
mirip batang sabun,
soda kue, putih telur,
dan sudah ada,
sejak abad ke-5.
Pada saat itu,
aku mendengar waktu
menguliti dirinya,
dengan sendok kayu.
Socrates duduk
di dasar kaca,
mencicipi absurditas
tanpa gula.
Ia menawarkanku napas
yang sudah disuling
dari abad Yunani kuno.
Di dinding pikiranku,
dunia menempel,
seperti sidik jari api
memindai hujan
dalam batok kaca
yang kemarau.
KEPADA DEMOKRITOS
Mungkinkah di dadamu,
miliaran hantu mikron
berlari ke barat,
seolah jagat yang dianggap berhala
pelan-pelan runtuh.
Dulu kau tafsirkan dunia ini
seperti lintasan ion,
kau hitung dengan cermat
serpihan semesta
yang saling menggigit
di antara kelahiran dan kematian.
Rupanya di zamanku,
dinding udara berubah jadi cakar,
menggaruk nadi realitas.
Atom-atom berdesingan,
seperti peluru,
menembus kepala,
membelah bahasa,
menjadi kebisingan porak-poranda.
Di ujung puisi ini
aku pun mengerti,
segala gerak, selalu menanjak,
dan melingkar,
menuju kehampaan.
IKAN-IKAN HERAKLITOS
Sungai berputar,
sebelum mataku
memancarkan kengerian,
sebagai luka bakar
pada siripnya yang kecil.
Entah dari mana,
seekor ikan menelan
cacing api yang hanyut,
lalu bergumam,
“setiap arus adalah
watakku sendiri,
dan menyimpan wajah
lain dari diam.”
Sementara air
mencoba kembali
ke pangkal batu,
tapi tak bisa,
dan dataran
yang menabur hujan,
kini menjadi cerita.
Di bawah arus,
akar dan nadi air
menghanyutkan cemas,
akankah limbah penyakit
dari epidermis sungai
mencelupkan dirinya,
seperti menyelamkan
ingatan tubuhku,
lalu menghitung mimpi
yang tenggelam
di dalamnya.