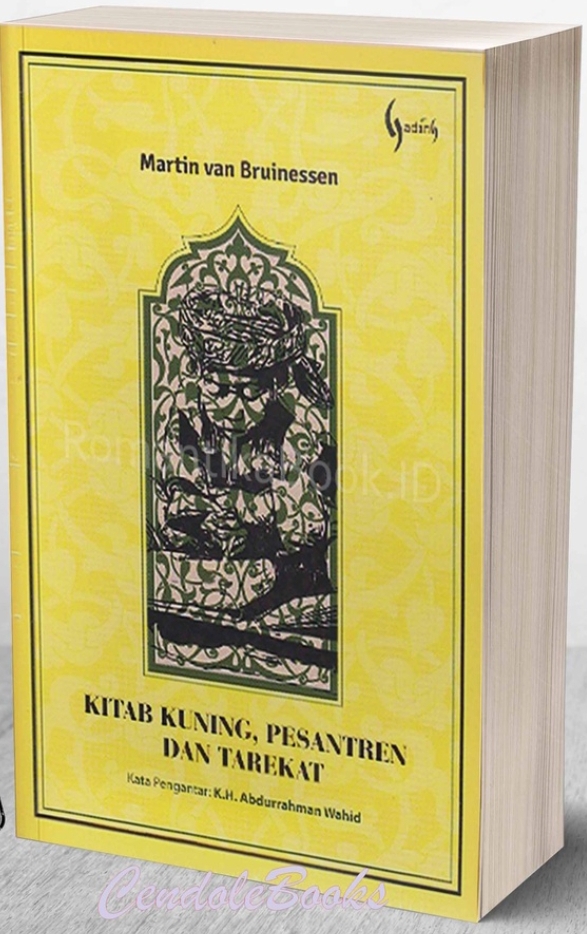Melalui buku Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat karya Martin van Bruinessen, kita belajar bagaimana cara yang tepat melihat perkembangan Islam di Indonesia, terutama dalam melihat pesantren.

Buku yang terbit pertama kali pada 1995 ini merupakan salah satu karya paling berpengaruh dalam studi tentang Islam tradisional di Indonesia. Ditulis oleh seorang akademisi Belanda yang meneliti secara langsung ke berbagai pesantren di Nusantara, buku ini mampu memberikan gambaran utuh, tajam, sekaligus empatik tentang tiga pilar utama tradisi Islam lokal: kitab kuning, lembaga pesantren, dan jaringan tarekat.

Di tengah derasnya modernisasi dan digitalisasi, buku ini terasa semakin relevan. Ia menyadarkan kita bahwa warisan Islam Indonesia tidaklah lahir dari ruang kosong, tetapi tumbuh dari perpaduan antara teks klasik, budaya lokal, dan praktik keagamaan yang terus hidup.
Kitab kuning, misalnya, bukan hanya buku pelajaran kuno, melainkan fondasi dari tradisi keilmuan yang mendalam dan disiplin. Pesantren tidak sekadar tempat menimba ilmu agama, tetapi juga pusat pembentukan karakter dan pemikiran. Sementara tarekat, yang sering disalahpahami, justru menjadi ruang penyucian jiwa dan pengasahan akhlak.
Di dalam buku ini, Martin memaparkan bagaimana proses masuknya ilmu-ilmu agama Islam dari sisi sejarah. Kemudian, ia juga menyajikan data sejarah pendidikan Islam Indonesia yang berbasis pada teks Arab yang sering disebut sebagai kitab kuning. Selain itu, juga budaya-budaya tarekat yang hingga saat ini tersebar merupakan hasil dari sejarah panjang yang tidak hadir secara instan.
Hal yang membuat buku ini istimewa adalah pendekatan van Bruinessen yang tidak arogan sebagai peneliti asing. Ia tidak datang untuk menghakimi, melainkan memahami. Dengan menelusuri langsung cara belajar santri, struktur sosial pesantren, hingga peran tarekat dalam kehidupan spiritual masyarakat, ia menunjukkan bahwa Islam tradisional bukanlah lawan modernitas, melainkan bentuk lain dari kecanggihan yang berbeda wajah.
Namun, membaca buku ini di zaman sekarang juga mengundang keprihatinan. Banyak dari tradisi yang dibahas dalam buku ini mulai terpinggirkan. Generasi muda Muslim hari ini lebih akrab dengan ustaz YouTube atau potongan ceramah viral di TikTok, ketimbang memahami secara utuh isi al-Jurumiyah atau Ta’lim al-Muta’allim. Popularitas perlahan menggantikan otoritas. Islam dikonsumsi sebagai slogan dan identitas, bukan sebagai jalan atau laku hidup yang mendalam.
Di sisi lain, pesantren hari ini dituntut untuk berubah dan membuka diri terhadap teknologi dan sains. Tuntutan ini wajar. Namun, jika perubahan itu meninggalkan ruh dan akar keilmuannya, maka pesantren bisa kehilangan perannya sebagai benteng nilai. Di sinilah pentingnya buku ini: mengingatkan kita pada nilai dasar dari tradisi keislaman yang telah terbukti tangguh menghadapi zaman.
Buku ini bukan sekadar karya ilmiah; ia adalah cermin. Ia mengajak kita merenung: apakah kita masih menghargai proses belajar yang penuh kesabaran? Apakah kita masih menghidupkan nilai-nilai sufistik dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita masih menganggap pesantren sebagai tempat pencetak pemikir, bukan sekadar penghafal?
Martin van Bruinessen, melalui karya ini, justru mengajarkan kita satu hal: jika orang luar saja bisa melihat kekayaan Islam Nusantara, mengapa kita sendiri malah melupakannya?