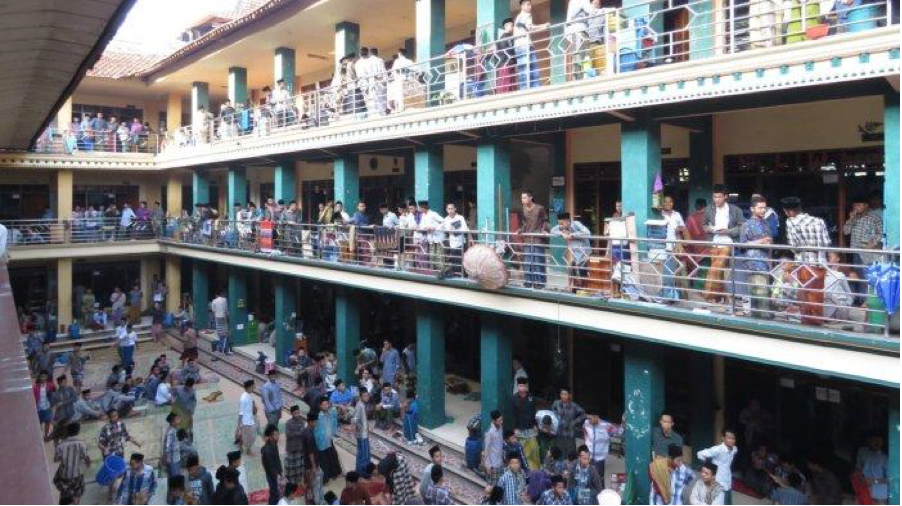Perbincangan tentang pesantren belakangan ini kembali ramai. Narasinya sering memojokkan kehidupan di pesantren, terutama berkaitan dengan relasi santri dan kiainya. Pengabdian santri, mulai dari membantu membangun pondok tanpa upah, mencium tangan kiai, hingga menaati segala petunjuk guru, kerapkali disamakan dengan praktik feodalisme, suatu istilah yang sarat dengan konotasi buruk.
Padahal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring, feodalisme dimaknai sebagai sistem sosial yang memberikan kekuasaan besar kepada bangsawan, atau sistem yang mengagungkan jabatan dan pangkat, bukan prestasi kerja. Jika makna itu dijadikan tolok ukur, istilah tersebut masih begitu kurang tepat untuk menggambarkan relasi di pesantren. Namun demikian, wacana publik kita kadung menggunakan istilah itu secara serampangan untuk menuding segala bentuk hierarki, termasuk hubungan kiai-santri.

Media dan Etika
Gelombang besar polemik ini kembali mencuat setelah tayangan Xpose Uncensored di Trans7 pada 13 Oktober 2025 yang menyoroti praktik di pesantren dengan nada provokatif. Akibatnya, tayangan tersebut menuai gelombang protes dan melahirkan tagar #BoikotTRANS7 di media sosial. Banyak kalangan pesantren yang menilai pemberitaan itu tidak adil, karena tidak menghadirkan suara dari pihak yang dituduh.
Sebagaimana yang sudah diingatkan Gus Dur dalam esainya, Pesantren sebagai Subkultur (2007), yang menjelaskan akan pendekatan ilmiah yang terbaik untuk memahami pesantren adalah pendekatan naratif dari dalam. Tanpa narasi internal, istilah seperti feodalisme mudah sekali untuk disalahgunakan dan menjadi alat stigma terhadap tradisi yang tidak sesuai dengan selera modernitas.
Pandangan serupa pun datang dari Ismail Fajrie Alatas, sosok antropolog yang menulis What Is Religious Authority? Cultivating Islamic Communities in Indonesia (2021). Dalam unggahan Instagram Story-nya pada 16 Oktober 2025, Alatas menyinggung kecenderungan kalangan modernis dan liberal yang “selalu merasa paling tahu dan paling benar, tetapi gagal memahami kerumitan tradisi sebagai himpunan hidup.”
Menurutnya, semangat egalitarianisme modern seringkali melahirkan kesalahpahaman terhadap hierarki tradisional, seolah setiap bentuk ketundukan selalu identik dengan praktik penindasan. Padahal, dalam masyarakat tradisional seperti pesantren, sebuah hierarki justru menjadi jalan penting untuk membentuk moral, pengetahuan, dan kepribadian.
Husein Muhammad dalam bukunya, Islam Tradisional yang Terus Bergerak (2019) menegaskan, bahwa kedudukan kiai tidak bersumber dari status sosial, melainkan dari moralitas, keluasan ilmu, ketulusan membimbing, serta kepribadiannya yang bersahaja.
Hal tersebut, juga sejalan dengan apa yang diungkapkan Zamakhsyari Dhofier dalam disertasinya, Tradisi Pesantren (2011), bahwa sikap tunduk santri kepada kiai bukanlah sikap alami, tetapi hasil proses panjang yang berdasar pada etika dan pertimbangan spiritual. Tradisi ini berpijak pada ajaran kitab Ta’lim al-Muta’allim, yang menempatkan adab sebagai dasar pencarian ilmu.
Dengan begitu, hierarki di pesantren bukanlah bentuk feodalisme yang selalu mengkultuskan sosok figur dengan segala jabatannya, melainkan struktur penghormatan terhadap ilmu dan moralitas. Ketundukan santri adalah latihan diri dalam kesabaran dan kerendahan hati.
Namun begitu, kepatuhan santri tentu tidak tanpa batas. Sebagaimana diingatkan KH Baha’uddin Nursalim (Gus Baha’), bahkan Nabi Musa pun pernah mempertanyakan tindakan gurunya, Nabi Khidir. Pertanyaan itu bukanlah suatu hal pembangkangan, melainkan upaya menjaga keseimbangan antara akal dan ketaatan. Dalam pesantren pun, kepatuhan selalu menyertakan kesadaran moral, bukan ketaatan yang membuta-tuli.
Dalam refleksi yang sama, Ismail Fajrie Alatas juga menulis, bahwa liberalisme, egalitarianisme, dan otonomi diri, sejatinya hanyalah “sebuah tradisi di antara berbagai tradisi.” Namun, sebagian kalangan liberal telah lupa, bahwa dirinya juga hidup dalam ruang tradisi tertentu. Mereka menganggap pandangan mereka adalah universal, padahal setiap pandangan berpijak pada konteks dan sejarahnya sendiri. Pertentangan antara modernitas dan tradisi sering kali macet di sini, keduanya sama-sama berbicara dari sistem nilai yang berbeda.
Kritik terhadap pesantren tentu perlu, terutama bila ada penyimpangan moral yang dilakukan oleh oknum kiai. Namun, mengeneralisasi penyimpangan sebagai ciri sistemik pesantren jelas tidak adil. Kritik yang lahir tanpa adanya crosscheck dan empati hanya akan mengulang kesalahan modernitas, yakni merasa netral, padahal bias. Seperti yang diingatkan Alatas, “menjadi terdidik bukan sekadar kemampuan mengkritik, tetapi kesadaran akan keterbatasan diri dan kerendahan hati untuk belajar dari yang lain.”
Pada akhirnya, menyebut pesantren sebagai lembaga yang melanggengkan praktik feodalisme adalah sebuah kesalahan konseptual yang lahir dari miskonsepsi bahasa dan dangkalnya pemahaman publik terhadap tradisi. Perlu disampaikan sekali lagi, bahwa relasi kiai-santri tidak bisa disamakan dengan hubungan bangsawan dan rakyat. Ia merupakan ikatan spiritual yang menempatkan ilmu di atas segalanya.
Sebagai penutup, seperti yang disampaikan Alatas dalam refleksi yang sama, “apa yang kita pelajari tak akan pernah sepenuhnya kita pahami. Pesona kehidupan selalu lebih besar dan rumit daripada keterbatasan akal kita.”
Tanpa kesediaan memahami pesantren dengan seimbang dan dari dalam, istilah seperti feodalisme hanya akan menjadi luka bahasa. Ia akan selalu menyakiti, bukan berusaha untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi