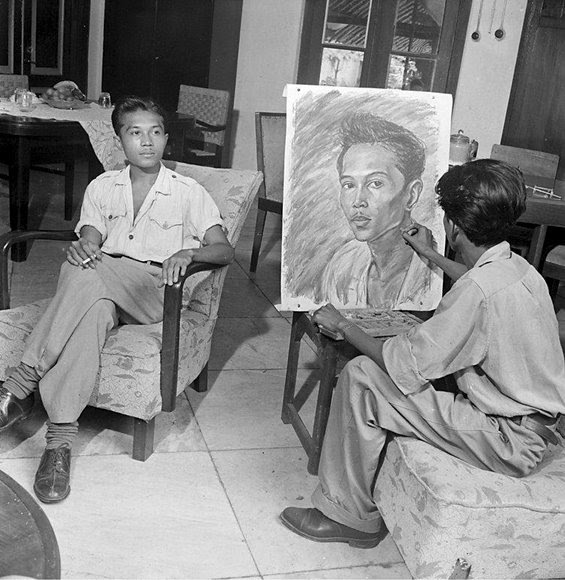I. Kebudayaan sebagai Tadarus Ingatan
Kebudayaan tidak hanya lahir dari produksi karya, tetapi dari kesadaran untuk mengingat. Dalam ingatanlah manusia menemukan kembali akar, arah, dan makna perjalanannya sebagai bangsa. Dalam ingatan pula bangsa Indonesia meneguhkan dirinya di hadapan perubahan zaman—bahwa identitas tidak tumbuh dari kekosongan, melainkan dari kesinambungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan.


Di situlah Semaan Puisi dan Haul 12 Sastrawan Indonesia 2025 menemukan maknanya. Ia bukan sekadar agenda budaya tahunan, melainkan peristiwa spiritual-kultural yang meneguhkan hubungan antara iman, imajinasi, dan ingatan. Ketiganya adalah poros yang menyangga keberlanjutan kebudayaan bangsa.
Dalam kegiatan ini, puisi tidak lagi dibaca sebagai teks estetik semata, melainkan sebagai doa yang bernyawa; haul tidak hanya menjadi acara mendoakan arwah, tetapi juga laku kultural untuk merawat jejak pemikiran dan nilai-nilai yang diwariskan oleh para sastrawan besar.
Kebudayaan, dengan demikian, tidak lagi hadir sebagai tontonan, tetapi sebagai tadarus kebangsaan. Sebagaimana para santri membaca kitab kuning untuk memahami hikmah hidup, masyarakat diajak membaca karya sastra dengan kesadaran spiritual: menyelami kata-kata sebagai zikir dan tanda-tanda kehidupan.
Di tengah dunia yang kian cepat dan bising, Semaan Puisi hadir sebagai ruang hening, tempat kata kembali memiliki daya suci. Dalam hening itulah kita menyadari bahwa puisi tidak pernah mati; ia hanya menunggu untuk dibacakan kembali dengan hati yang jernih.
II. Dari Tradisi Pesantren ke Tradisi Sastra: Zikir dalam Bahasa
Istilah semaan berasal dari khazanah pesantren. Ia adalah kegiatan membaca atau mendengarkan bacaan kitab suci secara bersama-sama, penuh kekhusyukan dan rasa takzim. Dalam tradisi itu, suara tidak hanya bunyi; ia menjadi jembatan antara manusia dan makna.
Maka ketika konsep semaan ini dihadirkan dalam dunia sastra, ia menghidupkan ulang hubungan yang telah lama terlupakan antara spiritualitas dan bahasa. Puisi menjadi kitab kehidupan, sementara penyair dan pendengarnya menjadi jamaah yang sama-sama menafsirkan ayat-ayat eksistensi.
Semaan Puisi mengubah cara kita berinteraksi dengan sastra. Ia bukan sekadar pembacaan publik, melainkan laku batin kolektif. Bait-bait puisi tidak dideklamasikan dengan gemuruh, tetapi dibaca dengan kesadaran penuh. Setiap kata menjadi seperti dzikir, setiap metafora menjadi jalan menuju makna yang lebih dalam.
Dalam konteks ini, puisi-puisi Chairil Anwar tidak sekadar tentang keberanian individu, tetapi tentang pergulatan manusia dengan takdir. Amir Hamzah tidak hanya menulis tentang cinta, tetapi tentang jarak antara hamba dan Tuhannya. Sapardi Djoko Damono tidak sekadar menulis kesunyian, tetapi mengajarkan cara mendengarkan bisikan alam yang sunyi.
Puisi, sebagaimana doa, hanya bermakna jika dibaca dengan hati yang hadir. Maka Semaan Puisi menjadi meditasi kultural yang menumbuhkan kesadaran baru: bahwa sastra bukan milik elite, melainkan milik seluruh umat yang mencari makna hidup.
III. Menyambung Ingatan Kolektif: Haul sebagai Ziarah Makna
Kegiatan Haul 12 Sastrawan Indonesia 2025 adalah bentuk ziarah makna. Ia mengajak kita menengok kembali dua belas nama yang membentuk peta kesadaran sastra dan kebudayaan Indonesia: Ajip Rosidi, Amir Hamzah, Asrul Sani, Chairil Anwar, H.B. Jassin, Hamzah Fansuri, Rivai Apin, Sanusi Pane, Sapardi Djoko Damono, Sitor Situmorang, Sutan Takdir Alisyahbana, dan W.S. Rendra.
Mereka adalah penjaga obor dari berbagai zaman. Dari Hamzah Fansuri, kita belajar bahwa bahasa dapat menjadi jalan menuju Tuhan. Dari Sanusi Pane, kita memahami pertemuan Timur dan Barat dalam jiwa Nusantara. Dari Chairil, kita belajar keberanian untuk menolak kejumudan. Dari Rendra, kita menyaksikan bahwa puisi bisa menjadi suara rakyat yang tertindas.
Haul menjadi wadah untuk menghadirkan mereka kembali ke tengah masyarakat, bukan dalam bentuk patung kenangan, melainkan dalam denyut kesadaran.
Kita membaca ulang karya mereka bukan untuk mengagungkan, melainkan untuk meneruskan percakapan yang belum selesai. Sebab kebudayaan sejatinya adalah percakapan antargenerasi—dialog panjang antara yang hidup dan yang telah mendahului.
Dengan membaca kembali puisi-puisi mereka dalam suasana haul, kita seolah berziarah bukan hanya ke makam, tetapi ke pusat makna. Kita menyapa jiwa-jiwa yang telah menyalakan api kesadaran bangsa dan berjanji untuk menjaga nyalanya.
IV. Haul sebagai Jalan Baru Merawat Jejak
Dalam tradisi Islam, haul adalah bentuk penghormatan kepada para pendahulu. Namun dalam konteks kebudayaan, haul menjadi metode merawat ingatan. Sastra sering lahir dari kesepian, tetapi hidup dari pembacaan ulang. Haul Sastrawan adalah bentuk kasih sayang kultural terhadap mereka yang telah menulis dengan darah dan doa.
Acara ini mengingatkan kita bahwa mengenang bukan sekadar ritual, melainkan laku kesetiaan terhadap nilai. Dalam haul, setiap bait yang dibacakan adalah doa, setiap penyair yang disebut adalah guru batin. Ia menghubungkan masa lalu dan masa kini, dunia fana dan kekekalan, imajinasi dan iman.
Melalui haul, bangsa Indonesia menemukan cara khasnya sendiri untuk menghormati intelektual—bukan dengan pidato dan patung, tetapi dengan pembacaan yang khusyuk dan berdoa bersama. Inilah spiritualitas khas Nusantara: menggabungkan zikir dengan estetika, doa dengan budaya.
V. Spiritualitas dan Estetika: Dua Sayap Kebudayaan
Banyak yang mengira iman dan seni adalah dua hal yang bertolak belakang. Padahal, keduanya berakar pada satu hal: kerinduan akan kebenaran. Iman adalah zikir menuju Tuhan; seni adalah pencarian bentuk bagi yang tak terucapkan.
Dalam Semaan Puisi, dua sayap itu bertemu. Puisi menjadi doa yang estetis; doa menjadi puisi yang metaforis. Di situlah bangsa ini menemukan wasatiyah kebudayaan—jalan tengah yang menolak ekstremisme dogmatik sekaligus skeptisisme nihilistik.
Asrul Sani pernah menulis bahwa “yang abadi dari seni bukan bentuknya, melainkan niatnya.” Niat inilah yang menjadi jantung dari Semaan Puisi dan Haul 12 Sastrawan Indonesia.
Di tengah fragmentasi digital, kegiatan ini menjadi ruang penyembuhan spiritual dan kultural—sebuah upaya menyeimbangkan nalar dan rasa, tafsir dan imajinasi, antara yang sakral dan yang profan.
VI. Menghidupkan Kembali Semangat Lesbumi
Lesbumi (Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia), yang didirikan pada awal 1960-an oleh Asrul Sani bersama Usmar Ismail dan Djamaluddin Malik, adalah tonggak sejarah penting dalam upaya menyatukan iman dan seni. Lesbumi lahir bukan sekadar sebagai reaksi politik terhadap Lekra atau Manikebu, tetapi sebagai tawaran epistemologis baru: bahwa kebudayaan adalah laku iman, dan iman adalah sumber daya cipta.
Asrul Sani menjadi figur sentral dalam gagasan ini. Ia, yang dikenal sebagai modernis dan humanis universal, justru menemukan kedalaman pemikirannya di rahim tradisi Islam Nusantara. Melalui Lesbumi, ia tidak lagi berbicara tentang seni untuk seni, melainkan seni untuk manusia dan Tuhan.
Semaan Puisi dan Haul 12 Sastrawan 2025 adalah gema kontemporer dari semangat Lesbumi: menjadikan puisi sebagai dzikir kolektif, dan haul sebagai ruang tafsir kebudayaan.
Seolah Asrul kembali bicara melalui waktu, mengingatkan bahwa bangsa ini hanya bisa bertahan jika seni dan iman berjalan beriringan.
VII. Asrul Sani dan Jalan Ketiga Kebudayaan
Dalam lanskap kebudayaan Indonesia pasca-1950-an, Asrul Sani berdiri di antara dua arus besar: realisme sosialis (Lekra) yang menundukkan seni di bawah politik, dan humanisme universal (Manikebu) yang cenderung elitis. Asrul memilih jalan yang lebih sulit—jalan ketiga. Ia melihat bahwa seni tidak boleh dijadikan alat politik, tetapi juga tidak boleh tercerabut dari masyarakat dan iman.
Lesbumi menjadi wadahnya untuk merumuskan humanisme religius: seni yang berpihak pada manusia karena berakar pada Tuhan. Dalam kerangka inilah Semaan Puisi dan Haul Sastrawan 2025 juga harus dibaca: sebagai upaya menghidupkan kembali warisan jalan ketiga itu di tengah zaman baru yang diwarnai krisis makna.
Ketika penyair-penyair hari ini berdiri membaca puisi di ruang haul, mereka sebenarnya sedang melanjutkan jejak Asrul—melakukan apa yang dulu ia impikan: menjadikan kata sebagai jembatan antara bumi dan langit.
VIII. Modernisasi Tradisi: Dari Situbondo ke Jakarta
Lesbumi bukan hanya konsep; ia gerakan nyata. Di berbagai daerah, kelompok teater pesantren seperti Al Badar di Situbondo mendapat sentuhan modern: tata lampu, musik, dan dramaturgi yang memperkaya tanpa merusak akar. Kisah Nabi dan hikayat sufistik dipentaskan dengan iringan dangdut Madura—seni rakyat yang bersenyawa dengan dakwah.
Spirit ini hidup pula dalam Semaan Puisi. Ketika santri, mahasiswa, dan penyair duduk bersama membaca Asrul Sani di pesantren, itu bukan sekadar peristiwa estetik. Itu adalah kelahiran ulang tradisi: modernitas yang bertemu dengan spiritualitas.
Inilah modernisasi tradisi yang dimaksud Asrul Sani: bukan menolak barat, tapi menyerapnya dengan cara kita sendiri—dengan kearifan lokal, dengan jiwa yang tunduk pada nilai.
IX. Haul sebagai Ekologi Makna: Mengingat untuk Menyembuhkan
Kita hidup di zaman amnesia kolektif, di mana memori sejarah digantikan oleh viralitas sesaat. Dalam kondisi demikian, kegiatan seperti Semaan Puisi dan Haul Sastrawan menjadi terapi budaya. Ia mengajarkan cara mengingat secara spiritual, bukan administratif.
Mengenang Ajip Rosidi, Amir Hamzah, Asrul Sani, Chairil Anwar, H.B. Jassin, Hamzah Fansuri, Rivai Apin, Sanusi Pane, Sapardi Djoko Damono, Sitor Situmorang, Sutan Takdir Alisyahbana, dan W.S. Rendra bukan sekadar nostalgia, tetapi cara memulihkan luka-luka makna bangsa. Setiap bait yang dibaca menjadi penawar bagi kegersangan rohani masyarakat modern.
Dalam haul, kita belajar bahwa mengingat adalah bentuk tertinggi dari kasih sayang. Sebab yang dilupakan, sejatinya adalah yang dianggap tak penting; sedangkan yang diingat, akan terus hidup dalam doa dan karya.
X. Generasi Baru dan Estetika Kesabaran
Bagi generasi muda, Semaan Puisi adalah madrasah estetika dan moral. Ia mengajarkan cara mendengarkan—keterampilan yang paling langka di dunia hari ini.
Mereka yang datang ke Semaan Puisi tidak hanya membaca, tetapi juga menyimak. Mereka belajar bahwa setiap kata punya ruh, dan setiap puisi punya waktu untuk tumbuh.
Dalam kebersamaan itu, sastra kembali menjadi ruang belajar kesabaran, di mana membaca adalah ibadah, dan mendengarkan adalah zikir.
Di sinilah makna sejati dari kebudayaan: bukan mengulang masa lalu, tetapi menanamkan akarnya ke hati generasi baru.
XI. Asrul Sani: Kreator yang Terlupakan
Sejarah sering menyukai tokoh-tokoh yang heroik dan biner. Karena itu, peran Asrul Sani di Lesbumi sering tertutup oleh kisah pertarungan Lekra vs Manikebu. Namun bila kita menelusuri lebih dalam, justru di Lesbumi-lah Asrul menunjukkan totalitasnya sebagai intelektual.
Ia bukan sekadar penulis naskah film atau pelopor Angkatan ’45, tetapi arsitek kebudayaan yang membangun jembatan antara Islam dan modernitas. Karyanya di Lesbumi—dari media Duta Masjarakat hingga majalah Gelanggang edisi baru—menjadi bukti bahwa modernisme bisa tumbuh dari pesantren, dan tradisi bisa beradaptasi dengan zaman.
Asrul Sani mengajarkan bahwa menjadi manusia modern tidak harus kehilangan akar, dan menjadi manusia beriman tidak berarti menolak kebaruan. Ia adalah kreator jalan ketiga, yang hari ini—melalui Semaan Puisi dan Haul Sastrawan—akhirnya dipanggil kembali ke dalam ingatan bangsa.
XII. Menyemai Harapan, Menjaga Cahaya
Pada akhirnya, Semaan Puisi dan Haul 12 Sastrawan Indonesia 2025 adalah laku menyemai harapan. Di tengah keretakan makna, ia mengajarkan kita untuk memperlambat langkah, menundukkan ego, dan mendengarkan kembali suara hati bangsa yang tenggelam oleh kebisingan modernitas.
Ia bukan sekadar penghormatan, tetapi pernyataan iman terhadap kata—bahwa puisi, sebagaimana doa, tidak pernah mati. Yang abadi dari seni, seperti kata Asrul Sani, bukanlah bentuknya, melainkan niatnya: niat untuk menyalakan cahaya, bahkan ketika dunia tak lagi percaya pada terang.
Dan karena itu, Semaan Puisi dan Haul 12 Sastrawan Indonesia 2025 bukanlah akhir dari ingatan, melainkan awal dari kesadaran baru: bahwa kebudayaan yang hidup adalah kebudayaan yang terus menyapa Tuhan dengan bahasa manusia.
*Artikel ini merupakan bagian dari buku acara Semaan Puisi dan Haul Sastrawan 2025 yang dilaksanakan di Makara Art Center Universitas Indonesia, Selasa (18/10/2025). Berisi enam tulisan yang juga diterbitkan di laman duniasantri.co secara bersambungan. Keenam naskah dalam buku ini adalah “Asrul Sani: Jalan Wasatiah Kebudayaan Indonesia” oleh Jamal D. Rahman; “Surat Semaan Puisi: dari Gelanggang ke Adakopi” oleh Mahwi Air Tawar; “Semaan Puisi: Melarikan dari Media Sosial, Kok Malah Ngurusi Mayat Penyair?” oleh Angin Kamajaya; “Lesbumi dan Revitalisasi Seni Budaya Pesantren” oleh Ngatawi Al-Zastrouw; “Kreator Jalan Ketiga yang Terlupakan: Refleksi Identitas Intelektual Asrul Sani” oleh Andy Lesmana; dan “Yang Mengusik Takdir” oleh Mukhlisin Ashar.