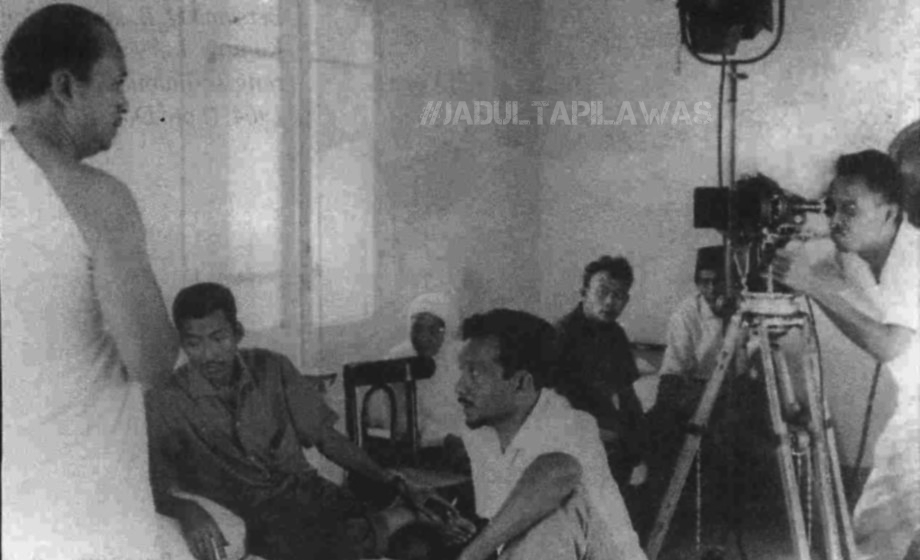Tuan Asrul,
Surat ini saya tulis bukan untuk membalas Surat Kepercayaan Gelanggang atau mengulangi pekik para pemuda tahun lima puluhan yang merasa baru saja menemukan suara dirinya. Tidak, Tuan. Surat ini lebih seperti secangkir kopi yang diseduh perlahan di Adakopi Original—sebuah kafe sederhana yang menjadi tempat kami tak hanya ngopi, tetapi juga bertukar ide, berdebat, dan mendirikan Semaan Puisi, yang kelak melanjutkan warisan pemikiran dan jejak kebudayaan yang Tuan tinggalkan.


Saya menulis ini sambil mendengarkan denting kecil sendok yang beradu dengan cangkir, seperti tanda seru yang tercebur ke dalam gelas. Di luar, azan magrib sudah turun perlahan ke dada malam. Ah, Tuan Asrul, tiba-tiba saya teringat bait puisi dalam “Lagu daripada Pasukan Terakhir”, Ah mengapa pada hari-hari sekarang, // matahari sangsi akan rupanya, dan tiada pasti pada cahaya // yang akan dikirim ke bumi.
Kali ini, Tuan Asrul, saya membayangkan Tuan mungkin sedang duduk di beranda surga, ditemani Chairil Anwar, Rivai Apin, dan Gus Dur, salah seorang cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Hadrotusyekh Hasyim Asy’ari, tempat engkau dulu juga berkhidmat di dalamnya.
Mungkin Tuan berempat masih memperdebatkan siapa yang lebih dulu menulis kalimat yang kemudian mengubah arah angin sastra Indonesia. Atau, mungkin, Chairil sedang menertawakan keseriusan Tuan dengan gaya khasnya: “Asrul, jangan terlalu percaya pada kata-kata. Mereka licin, seperti ikan di tangan penyair lapar.”
Tapi Tuan tentu tahu, di bawah sini, kami—anak-anak yang lahir di zaman gawai dan jaringan nirkabel—masih berusaha memahami arti “merdeka” yang pernah Terjadi Tuan tulis. Sebuah surat yang, bagi kami, adalah kitab kecil tentang bagaimana menjadi manusia yang tidak hanya menulis puisi, tetapi juga menulis dirinya sendiri di dalam sejarah.
Di Adakopi Original, kami menyebutnya Semaan Puisi. Nama itu, Tuan, mengandung kebetulan yang disengaja. Kami mengambil tradisi semaan dari pesantren: membaca kitab, mendengarkan bacaan, menyimak, lalu menadaburinya bersama. Tapi kali ini, kitab kami adalah kumpulan puisi, makalah kebudayaan, atau obrolan tentang siapa yang lebih cocok disebut “penyair sesungguhnya”: yang lahir dari penderitaan, atau yang lahir dari algoritma.
Suatu malam, di antara aroma kopi tubruk dan asap rokok kretek, Zaky Mubarok—dosen dan penulis yang lebih suka dipanggil Angin Kamajaya—bertanya, “Apa bedanya gelanggang kalian dulu dengan semesta kopi kami sekarang?”
Pertanyaan itu jatuh ke meja seperti biji kopi yang gagal disangrai: kecil tapi menggelegar.
Saya lalu mencoba menjawab, meskipun saya tahu, jawaban apa pun mungkin terdengar konyol di telinga Tuan. “Mungkin bedanya cuma satu, Tuan,” kata saya dalam hati, “kalian menulis surat di masa merdeka, kami menulis puisi di masa kehilangan makna kemerdekaan.”
Tuan Asrul, saya tahu bahwa ketika Tuan bersama Gelanggang menulis Surat Kepercayaan Gelanggang, tidak sedang berusaha membentuk kelompok elite sastra. Tuan hanya mencari tempat berpijak di antara dua kutub: kebudayaan yang mewarisi tradisi kolonial, dan kebudayaan nasional yang sering kali tersesat dalam jargon politik kaku.
Saya masih ingat kalimat Tuan yang begitu jernih: “Dalam proses kreatif, seniman tidak hanya menciptakan karya, tetapi juga menemukan dan membentuk jati dirinya. Perjuangan untuk menghasilkan karya adalah perjuangan untuk menjadi manusia yang utuh.”
Namun, izinkan saya jujur: zaman kami ini aneh. Kami hidup di masa di mana kebudayaan bukan lagi ruang, tapi konten. Terkadang, kami membaca bukan untuk memahami, melainkan untuk mencari kutipan yang bisa dipajang di Instagram Story. Kalau dulu Tuan dan Chairil memperdebatkan peran kebudayaan nasional dalam menghadapi kolonialisme Barat, sekarang kami memperdebatkan algoritma yang bisa membuat puisi Rendra kalah viral dari video apa pun yang dianggap trending.
Tentu, perbandingan ini terdengar konyol, tapi begitulah kenyataan zaman kami: sebuah gelanggang baru yang tidak lagi butuh manifesto tebal, tapi cukup dengan tagar yang kuat.
Kami tidak menolak modernitas, Tuan. Kami hanya mencoba, seperti Tuan dulu, mencari jalan tengah. Maka di Adakopi itu, sebelum kami membaca puisi, kami selalu membaca Surat Yasin, bertahlil, dan bertawassul. Bukan karena kami hendak mengislamkan puisi, tetapi karena kami takut kehilangan ruh yang membuat kami bisa menulis dengan hati yang masih berdenyut.
Zaman ini membuat segalanya cepat, Tuan. Bahkan kesedihan pun bisa diunduh dalam bentuk status singkat. Tapi di antara kecepatan itu, kami mencari jeda. Kami membaca Asrul Sani dan sejumlah sastrawan yang gagasannya susah dirubuhkan—dengan cara yang sama kami menyeruput kopi: pelan, beraroma, dan kadang terlalu pahit untuk ditelan sekaligus.
Tuan Asrul,
Tuan dulu pernah berselisih paham dengan Sutan Takdir Alisjahbana (STA)—tokoh modernis yang percaya pada evolusi budaya. Tuan menuduhnya sebagai “manusia yang mengelap-ngelap kebudayaan,” sementara ia menuduh Tuan terlalu romantik terhadap masa lalu. Namun, di balik perdebatan itu, sesungguhnya kalian membicarakan hal yang sama—cinta pada kebudayaan Indonesia—hanya saja dengan logat yang berbeda.
Sekarang, bayangkan, Tuan. Kalau STA masih hidup hari ini, mungkin ia akan membuat kanal YouTube berjudul “Menjadi Modern bersama STA,” dengan tagline: “Budaya itu evolusi, bukan nostalgia.” Sementara Tuan, mungkin akan punya podcast berjudul “Lesbumi Talks: Di Antara Iman dan Imajinasi.”
Saya ragu, apakah dunia digital ini benar-benar tempat yang bisa menampung “jiwa merdeka” seperti yang Tuan-tuan perjuangkan? Sebab di sini, kebebasan sudah berubah bentuk: dari keberanian berkata benar menjadi keberanian menggaet follower.
Namun, izinkan saya kembali ke soal “debu kebudayaan.” Tuan menuduh STA mengelap-ngelap kebudayaan, seolah kebudayaan itu cermin yang harus selalu mengilap. Hari ini, kami justru hidup dalam kebudayaan yang terlalu bersih, terlalu mengilap, sampai kita tak lagi melihat wajah sendiri di dalamnya.
Debu yang dulu Tuan hindari, kini hilang sama sekali. Padahal, bukankah debu itu yang membuat sejarah terasa nyata? Kami di Adakopi percaya, sedikit debu adalah tanda kehidupan. Kami biarkan kata-kata berdebu, agar terasa nyata di lidah.
Malam itu, setelah kami membaca Surat Kepercayaan Gelanggang, Gilang—salah satu pendiri Semaan Puisi—bertanya dengan polos, “Apakah mungkin menulis puisi tanpa ideologi?”
Saya teringat Tuan, yang memilih tidak menandatangani Manifes Kebudayaan maupun ikut ke Lekra. Tuan memilih jalan tengah: mendirikan Lesbumi.
Sikap Tuan itu, bagi kami, seperti secangkir kopi tanpa gula: pahit, tapi jujur. Tuan tidak menolak modernitas, tapi juga tidak larut di dalamnya. Tuan hanya memilih, sebagaimana Gus Dur kelak mengatakan, jalan kebudayaan yang berpihak pada kemanusiaan.
Di Adakopi Original, kami tidak menulis manifesto. Kami hanya menulis catatan kecil di buku tamu: “Puisi adalah doa yang tidak selesai dibaca.”
Kami tahu, itu terdengar klise. Tapi bukankah kebudayaan selalu lahir dari hal-hal yang diulang terus-menerus sampai jadi tradisi?
Maka setiap Kamis malam, kami membaca tahlil dan Yasin, lalu membuka buku puisi. Kami percaya, di antara ayat dan bait, ada ruang yang sama: ruang sunyi tempat manusia berbicara dengan dirinya sendiri. Dan bukankah itu pula, Tuan, inti dari kebudayaan?
Tuan Asrul yang selalu saya hormati,
Izinkan saya menulis dengan sedikit keberanian tentang pertikaian antara ideologi dan iman, antara sastra yang memihak rakyat dan sastra yang memihak langit.
Saya tahu, Tuan tidak pernah menyukai dikotomi semacam itu. Bahkan di saat para kawan di Gelanggang terpecah—sebagian ke Manikebu, sebagian menyeberang ke Lekra—Tuan memilih berdiri di tengah, seperti orang yang tidak mau ikut rebutan panggung tapi justru menulis skenario tentang para pemainnya.
Saya membaca kembali pidato-pidato Tuan setelah 1963. Nada suaranya tenang, tetapi di balik ketenangan itu saya mendengar gelombang besar: semacam kekecewaan yang dibungkus doa.
Betapa lelahnya menjadi penyair yang ingin jadi manusia utuh di tengah negara yang sedang belajar menjadi negara—di tengah ideologi yang saling meniadakan.
Tuan,
Bagi saya, Manikebu adalah sejenis jeritan spiritual: jeritan orang yang tidak ingin puisi dijadikan alat, tapi juga tidak ingin puisi menjauh dari manusia. Tuan memilih jalan Lesbumi bukan karena menolak semangat Manikebu, melainkan karena tahu: seni yang berpihak pada kemanusiaan tidak perlu dibungkus dalam pernyataan politik.
Mengutip makalah Jamal D. Rahman, “Lesbumi, sebagaimana engkau dirikan, Tuan, bukan sekadar lembaga, melainkan ikhtiar moral untuk menyelamatkan seni dari kerak ideologi. Jamal D. Rahman menyebutnya jalan wasatiah; jalan tengah yang tidak netral, tetapi penuh makna —jalan yang mencari keseimbangan antara warisan dan penciptaan, antara iman dan kebebasan, antara transedensi dan sejarah. Ia tidak memilih Barat atau Timur, tidak tunduk pada politik sebagai panglima, dan tidak larut dalam sekularisme yang memisahkan iman dari ekspresi budaya. Sejak awal, Asrul Sani menapaki jalan wasatiah: sebuah jalan tengah yang bukan kompromi, melainkan sintesis batin antara warisan dunia, kebebasan manusia, dan nilai-nilai spiritual Islam.”
Sebuah ‘wadah kebudayaan religius yang berusaha mengembalikan seni kepada spiritualitas kemanusiaan.’ Kini kami, di Semaan Puisi, hanya mencoba menggemakan kembali napas itu.”
Lesbumi adalah anomali sejarah yang indah: di saat kebudayaan direbut antara kiri dan kanan, antara realisme sosial dan eksistensialisme, Tuan datang membawa sajadah dan naskah skenario. Tuan menunjukkan bahwa agama tidak menghalangi kreativitas, justru menjadi sumur di mana imajinasi bisa disiram setiap kali kering.
Tuan percaya, kebudayaan membutuhkan naungan spiritualitas agar tidak kering kerontang oleh ideologi. Keyakinan semacam itu, bagi saya, jauh lebih revolusioner daripada semua manifesto yang pernah ada. Sebab, sikap Tuan yang memilih mengalir di antara dua kutub bukan lahir dari rasa takut pada ideologi, melainkan dari kesadaran bahwa kebudayaan tidak dapat diselamatkan hanya dengan ideologi; ia hanya bisa dipeluk dan dijaga dengan cinta. Cinta kultural itulah yang mendorong Tuan mendirikan Lesbumi, dan kemudian, memutuskan untuk berangkat haji, sebuah ziarah yang disaksikan kawan sezaman sebagai pencarian kemurnian diri dan yang membuat Tuan kembali dengan wajah yang “lebih teduh.” Kisah Tuan ke Tanah Suci adalah bab yang indah dalam biografi seorang sastrawan. Mereka menulis: “Asrul Sani naik haji, dan pulang dengan wajah yang lebih teduh.”
Teduh, Tuan. Bukan berubah, bukan menyesal, tapi teduh.
Mungkin di antara thawaf dan sa’i itu, Tuan menemukan jawaban yang tak sempat terjawab di Gelanggang: bahwa manusia yang utuh bukanlah yang berani melawan, tapi yang berani memaafkan.
Saya membayangkan adegan Tuan di depan Kakbah. Tidak ada lagi “seniman merdeka,” “pejuang Lekra,” atau “penandatangan Manikebu.” Semua hanyalah hamba. Dan mungkin, di saat itulah Tuan tersenyum dan berkata pelan, “Seni yang sejati adalah ibadah yang terselubung.”
Pernyataan itu, bagi saya, adalah manifes paling sunyi yang pernah lahir di sejarah sastra Indonesia.
Ketika Tuan kembali, Tuan tidak berkoar-koar tentang pencerahan. Tuan hanya bekerja—menulis, menyutradarai. Tapi sejak itu, ada aroma ziarah dalam setiap karya Tuan. Bahkan ketika Tuan menulis skenario film seperti Titian Serambut Dibelah Tujuh, saya merasakan sejenis ketenangan spiritual di balik narasi yang kelam. Seolah Tuan ingin berkata: dunia ini boleh ribut, tapi hati seniman harus tetap jernih.
Tuan Asrul,
Dalam sejarah kebudayaan kita, orang-orang seperti Tuan sering terlupakan. Orang mengingat Chairil karena puisinya yang meledak-ledak, mengingat Pramoedya karena perlawanan politiknya, tapi jarang yang mengingat Tuan sebagai penyambung dua dunia: dunia batin dan dunia sosial, dunia doa dan dunia layar lebar.
Namun, percayalah, di antara anak-anak muda di Adakopi Original, nama Tuan masih sering disebut. Kami membaca karya Tuan bukan sebagai nostalgia, tapi sebagai panduan moral: bagaimana tetap waras di tengah kegilaan zaman.
Ketika kami lelah menghadapi dunia yang serba tergesa, kami membaca karya Tuan. Ketika kami bingung harus memilih antara menjadi religius atau modern, kami mengingat jalan tengah Tuan.
Dan ketika kami ragu, apakah puisi masih penting di tengah suara mesin dan iklan digital, kami membaca kalimat Tuan: “Seniman tidak hanya menciptakan karya, tetapi juga menemukan dan membentuk jati dirinya.”
Kalimat itu, Tuan, adalah azan kecil bagi kami yang hidup di tengah kebisingan algoritma.
Saya sering berpikir, kalau Tuan hidup hari ini, mungkin tidak akan membuat Surat Kepercayaan Gelanggang. Mungkin akan membuat film pendek berjudul “Manifesto di Tengah Kopi”, atau “Sajak-sajak di Layar Gawai.”
Mungkin Tuan akan berkata, “Kebudayaan bukan soal bentuk, tapi soal arah niat.”
Kami, generasi yang lahir jauh setelah Tuan, hanya bisa berusaha mengikuti jejak itu—meski dengan langkah yang kadang terantuk di batu iklan dan status viral.
Tuan Asrul,
Izinkan saya menutup bagian ini dengan kisah kecil. Suatu malam, di Adakopi, listrik padam. Lampu mati, Wi-Fi putus, dan semua orang diam. Dalam gelap itu, Beni Satria, salah satu pendiri Semaan Puisi, tiba-tiba berkata pelan, “Mungkin beginilah rasanya jadi penyair zaman Asrul Sani. Tidak ada cahaya, tapi tetap menulis.”
Kami semua tertawa, lalu menyalakan lilin. Di bawah cahaya kecil itu, kami membaca puisi-puisi lama. Bukan untuk romantisme, tapi untuk belajar tenang.
Saya rasa, di sanalah kami paling dekat dengan Tuan—bukan ketika membaca karya Tuan, tapi ketika merasakan keheningan yang Tuan wariskan. Keheningan yang tidak menolak modernitas, tapi juga tidak tunduk padanya. Keheningan yang tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus menyeruput kopi.
Kini biarlah surat ini saya akhiri dengan cerita yang sederhana, tapi penuh makna: tentang bagaimana pertemuan kecil di antara kopi, doa, dan puisi perlahan berubah jadi tradisi.
Pada mulanya, kami hanya sekelompok anak muda di Adakopi Original. Kami datang dengan niat sederhana: membaca, berbagi, dan menertawakan hidup. Tapi dari pertemuan kecil itu, tumbuhlah sesuatu yang jauh lebih hangat: Semaan Puisi.
Hari ini Tuan Asrul yang terkasih, Selasa, 28 Oktober 2025, bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda. Kami merayakan Haul Sastrawan dan Ulang Tahun Kedua Semaan Puisi—kali ini tidak lagi di Adakopi Original, tapi di Makara Art Center, Universitas Indonesia. Di sanalah kami, para penyair, santri, dan pencinta kopi, berkumpul untuk mengenangmu—bukan dengan air mata, tapi dengan tawa dan doa.
Acara ini dibuka oleh budayawan Ngatawi Al-Zastrouw, sosok yang melanjutkan langkah Anda, menghidupkan kembali denyut Lesbumi. Suatu waktu, beliau berkata, “Lesbumi itu seperti lilin yang tak pernah benar-benar padam, hanya kadang tertiup angin sejarah. Tugas kita bukan menciptakan lilin baru, tapi menjaga agar nyalanya tetap ada.”
Tuan Asrul,
Surat ini terlalu panjang, tapi biarlah saya akhiri dengan pengakuan sederhana: Kami menulis dan membaca bukan semata untuk dikenang, tapi agar kebudayaan tidak kehilangan arah. Kami ingin menjadi bagian dari nyala kecil itu—nyala yang Tuan wariskan.
Kami tahu, kebudayaan tidak bisa diselamatkan dengan pidato, tapi dengan kesetiaan. Dan barangkali, inilah bentuk kesetiaan kami: terus membaca puisi, terus menyalakan lilin, terus percaya bahwa antara kata dan doa ada hubungan rahasia yang membuat manusia tetap menjadi manusia.
Depok Terluar, 2025.
*Artikel ini merupakan bagian dari buku acara Semaan Puisi dan Haul Sastrawan 2025 yang dilaksanakan di Makara Art Center Universitas Indonesia, Selasa (18/10/2025). Berisi enam tulisan yang juga diterbitkan di laman duniasantri.co secara bersambungan. Keenam naskah dalam buku ini adalah “Asrul Sani: Jalan Wasatiah Kebudayaan Indonesia” oleh Jamal D. Rahman; “Surat Semaan Puisi: dari Gelanggang ke Adakopi” oleh Mahwi Air Tawar; “Semaan Puisi: Melarikan dari Media Sosial, Kok Malah Ngurusi Mayat Penyair?” oleh Angin Kamajaya; “Lesbumi dan Revitalisasi Seni Budaya Pesantren” oleh Ngatawi Al-Zastrouw; “Kreator Jalan Ketiga yang Terlupakan: Refleksi Identitas Intelektual Asrul Sani” oleh Andy Lesmana; dan “Yang Mengusik Takdir” oleh Mukhlisin Ashar.