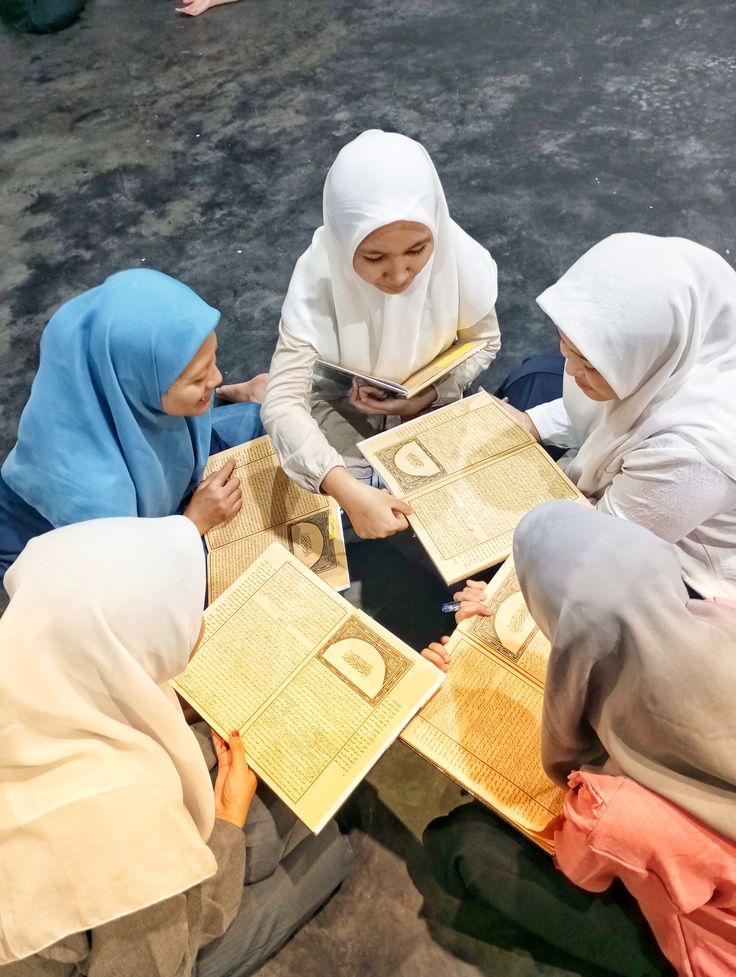Persoalan haid selalu menempati posisi yang unik sekaligus rumit dalam khazanah fikih Islam. Ia adalah ranah hukum yang tidak hanya bersinggungan dengan norma agama, tetapi juga inheren dengan realitas biologis perempuan yang begitu personal dan variatif.
Kerumitan muncul tatkala kita mencoba merekonsiliasi antara formula yang dibakukan dalam teks-teks klasik dengan dinamika empiris yang dihadirkan oleh tubuh perempuan.

Secara definitif, fikih klasik—terutama dalam tradisi Syafi’iyyah—telah memasang pagar batasan yang tegas: minimal haid adalah satu hari satu malam (24 jam) dan maksimal lima belas hari. Darah yang keluar di luar rentang waktu ini secara otomatis digolongkan sebagai istihadhah (darah penyakit) dan tidak membebaskan perempuan dari kewajiban ritual ibadah.
Di sinilah letak tegangan antara ketetapan ulama dan realitas. Bagaimana kita menyikapi kasus seorang perempuan yang secara ajek (konsisten) mengalami pendarahan kurang dari 24 jam, atau sebaliknya, selalu melampaui batas 15 hari? Jika kita bersikukuh pada teks baku, darah tersebut bukanlah haid. Namun, bukankah bagi perempuan, pola pendarahan merupakan kebiasaan biologisnya?
Menjawabnya dengan dogma teks semata terasa kurang memuaskan. Batasan minimal dan maksimal yang kita warisi, sejatinya, adalah hasil ijtihad yang lahir dari observasi dan konteks zaman para ulama terdahulu. Imam Syafi’i, misalnya, merumuskan qawl jadid-nya dengan berpijak pada realitas perempuan di Mesir. Artinya, formula tersebut adalah produk sosio-biologis tertentu, bukan dogma yang absolut dan bebas konteks.
Jika dasar penetapan hukum adalah observasi, maka seharusnya observasi kontemporer dan realitas individual juga memiliki hak untuk didengarkan. Fikih, pada dasarnya, adalah upaya sistematisasi norma agar sejalan dengan tujuan syariat, bukan menciptakan kerangka kaku yang memaksa tubuh tunduk pada angka-angka mati.
Ketegangan ini ternyata telah diakui dan dibahas secara mendalam dalam tradisi fikih itu sendiri. Dalam Kitab Majmu’ (Syarh al-Muhadzdzab), kita menemukan adanya tiga pandangan utama yang menyoroti dialektika ini.
Pertama, pendapat konservatif yang dipegang oleh Imam al-Haramayn dan Imam ar-Rafi’i. Mereka memilih untuk mengabaikan keadaan individual yang menyimpang. Yang diikuti tetaplah ketetapan baku. Alasannya, jika setiap anomali diakui, dikhawatirkan akan muncul kesemrawutan (al-fasad) dan rusaknya kebiasaan baku (rusaknya adat). Prioritas di sini adalah ketertiban umum di atas pengakuan realitas individual.
Kedua, pendapat realis (tahqiqi), yang diperjuangkan oleh ulama tahqiq seperti Abu Ishaq al-Isfirani dan Qadhi Husayn. Pendekatan ini secara lugas menyatakan bahwa keadaan wanita itu diperhitungkan. Yang dijadikan pijakan adalah realitas empirisnya. Jika pola pendarahan tertentu sudah menjadi kebiasaan rutinnya, maka itulah tanda haid dan sucinya.
Ketiga, pendapat moderat, yang memilih kompromi, yaitu realitas individu diakui hanya jika ia selaras dengan pendapat ulama salaf yang juga berpegangan pada realita.
Imam al-Haramayn dan ar-Rafi’i akhirnya lebih memilih jalan pertama, sebuah pilihan yang menegaskan kecenderungan fikih untuk mempertahankan struktur dan keteraturan normatif demi menghindari kebingungan. Namun, bagi fikih kontemporer, pandangan kedua—yang mendahulukan realitas empiris—menawarkan jalan keluar yang lebih menjanjikan dan berkeadilan.
Fikih semestinya menjadi alat untuk melayani keadilan, bukan alat untuk membebani. Mengakui pola pendarahan yang konsisten sebagai haid, meskipun ia berada di luar batasan baku, adalah bentuk pengakuan atas kedaulatan biologis perempuan. Memaksa seorang perempuan untuk salat dalam kondisi yang secara biologisnya merupakan pendarahan yang rutin, hanya demi patuh pada angka 24 jam atau 15 hari, adalah menciptakan kesulitan (haraj) yang tidak semestinya.
Ketika batasan ulama terdahulu dipahami sebagai metodologi yang kontekstual, bukan sebagai kebenaran mutlak, maka pintu ijtihad terbuka lebar. Kita dapat dan harus berani menguji ulang asumsi-asumsi tersebut dengan data ilmiah dan empiris yang lebih luas saat ini.
Intinya, perdebatan ini bukan sekadar tentang darah, melainkan tentang sejauh mana fikih mau dan mampu beradaptasi dengan keragaman ciptaan Tuhan. Keberanian untuk mengakui realitas perempuan adalah langkah awal menuju fikih yang lebih berkeadilan dan relevan bagi setiap individu.